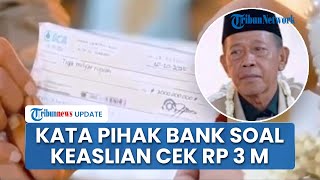Hikmah Ramadan 2021
Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Jatim, Haqqul Yaqin: Puasa Momen Transendensi Humanisme Islam
Dengan tegas dinyatakan dalam QS. 51:56 bahwa tujuan penciptaan manusia untuk senantiasa beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah.
DI tengah pandemi yang masih sulit diprediksi kapan akan berakhir, ekspresi kemanfaatan beragama akan selalu dilihat pada ukuran-ukuran kemanusiaan.
Sisi kemanusiaan dipandang sebagai dasar segala aktivitas, sehingga spiritualitas maupun ritus akan selalu disandarkan pada konteks kemanusiaan.
Komitmen ini sebagai upaya menemukan kembali makna dasar agama yang dapat membebaskan manusia dari segala determinisme yang terdapat dalam pranata kehidupan modern.
Di sinilah arti penitng agama sebagai sarana pembebasan. Saat ini agama dituntut menunjukkan idealismenya dengan memberikan kontribusi praktik sosial yang lebih memberi kepedulian lebih pada nilai-nilai kemanusiaan.
Ibadah puasa sebagai ritus yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan tentunya memiliki momentum penting dalam upaya melakukan rekonstruksi dan kontekstualisasi ajaran Islam hubungannya dengan pemahaman di atas. Inti pengalaman keagamaan adalah Tuhan.
Dalam Islam pembacaan syahadat merupakan ekspresi ikrar ilahiyah akan komitmen pendasaran setiap perilaku manusia dalam mewujudkan nilai ideal moral agama (Isma’il Raji al-Faruqi).
Dengan syahadat seorang hamba mengikrarkan diri untuk senantiasa mengabdikan tindakan pada upaya-upaya mewujudkan inti ajaran Islam yang penuh kasih dan sayang.
Hal utama yang menjadi pesan moral ibadah puasa adalah mencegah atau menahan diri (imsak). Tentu saja makna ini tidak hanya dibatasi pada berhentinya mengkonsumsi makanan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari.
Kata imsak harus diarahkan pada pemaknaan yang lebih substansial sebagai upaya mewujudkan kedalaman makna
spiritual ajaran Islam, salah satunya adalah nilai-nilai kemanusiaan.
Ibadah apapun yang diajarkan dalam Islam sejatinya dalam rangka memenuhi hajat manusia, yaitu kebutuhan
akan kebaikan dan kemanfaatan. Karena itu perintah puasa dalam ayat al-Qur’an diikuti
dengan kata taqwa.
Takwa merupakan elemen penting yang bekerja sebagai homeostatis demi terciptanya equilibrium dalam kehidupan manusia.
Sepanjang masa manusia menjalani hidup, sudah pasti akan dibenturkan dengan fonemena aral yang tidak saja menguji keimanan seseorang, bahkan menggerusnya sampai pada titik minimal.
Pada kondisi ini manusia senantiasa diserukan untuk bertakwa di mana salah satunya dilakukan melalui ritual puasa.
Dengan puasa dimungkinkan terjaganya kondisi konstan sehingga ritme kehidupan dapat bergerak normal.
Imsak dalam puasa berperan sebagai kontrol terhadap kerja dua substitusi diri manusia yang dalam praktiknya sering
bertentangan, yaitu rasio dan nafsu.
Dalam konteks ini, takwa diartikan sebagai resistensi melawan tensi-tensi moral untuk tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama.
Transendensi Nilai Kemanusiaan
Dengan tegas dinyatakan dalam QS. 51:56 bahwa tujuan penciptaan manusia untuk senantiasa beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Penegakan ibadah dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah.
Kebajikan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk kemaslahatan dirinya, begitu pula, setiap tindakan kejahatan akan merugikan diri dan orang lain. Oleh karena itu manusia tidak boleh dibiarkan menyendiri dalam hasrat-hasrat subjektifitasnya.
Manusia harus senantiasa diajak melakukan kebajikan agar mampu melepaskan diri dari kecenderungan
memberikan penilaian yang salah terhadap kualitas dan validitas suatu amal perbuatan.
Setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia, dengan demikian, sejatinya untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan manusia yang aman dan nyaman.
Determinasi ibadah sekaligus ekspresi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu setiap pelaksanaan ibadah
tentunya akan mengarah pada upaya mewujudkan cita-cita ideal tersebut.
Namun begitu, tidak diingkari bahwa dalam praktiknya, sebagaimana diingatkan Allah dalam QS. 18:103-105, bahwa terdapat segolongan manusia yang menilai perbuatannya sebagai amal baik tapi di akhirat kelak tidak diganjar dengan pahala, bahkan tidak memiliki bobot apapun di hari pengadilan.
Fazlur Rahman (1996) menggambarkan orang-orang yang merugi tersebut dengan korban- korban penipuan diri. Mereka menjadi korban dari organisasi atau institusi tertentu yang tampak menyerukan kebaikan, tapi hakikinya membuat kerusakan dan kejahatan.
Imajinasi pemahaman keagamaan yang menistakan nilai-nilai kemanusian dan keadilan, apalagi dengan senagaja menghilangkan nyawa orang lain, substansinya merupakan wujud sikap aniaya (QS. 2:11-12).
Angan-angan mendapatkan surga Allah dengan menumbalkan jiwa dan hak hidup orang lain tak lebih sebagai tindakan lalim dan kejahatan yang nyata (QS. 4:123).
Sifat manusia sebagai makhluk yang lemah (QS. 4:28), cenderung secara kontinu melakukan kemaksiatan dan bertindak melampaui batas (QS. 75:5) selalu tergesa-geasa (QS. 21:37) dan senantiasa beralih dari satu titik ekstrem ke titik ekstrem lainnya (QS. 10:12) mencerminkan terjadinya tensi moral yang luar biasa dalam hidup manusia.
Namun begitu, manusia pada dasarnya merupakan makhluk teomorfis. Artinya, di balik segala kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, manusia masih menyimpan harta karun dalam dirinya, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Masih ada sesuatu yang suci dalam diri manusia.
Fakta inilah yang memberikan harapan dan optimisme yang memungkinkan manusia meraih derajat yang lebih tinggi dari makhluk yang lain, termasuk malaikat sekalipun. Sebaliknya, pada saat yang sama manusia bisa menjadi seperti setan dan lebih hina dari binatang.
Manusia sebagai sosok makhluk yang diciptakan dalam kesempurnaan (QS. 95:4) telah dikaruniai suatu kualitas keutamaan dan diberi tugas menjadi wakil Tuhan (khalifah) di muka bumi dengan mandat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan.
Artinya, pada perspektif ini manusia senantiasa dituntut untuk membuktikan kemampuannya mengembangkan potensi dirinya guna memenuhi tugasnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi.
Di sinilah letak strategis eksistensi manusia, sehingga dalam al-Qur’an kata insan disebut lebih dari enam puluh kali.
Demikianlah, manusia tercipta sebagai makhluk yang dinamis, yang bisa mewujud sebagai makhluk yang senantiasa menghamba pada kebaikan (seperti halnya malaikat) atau senantiasa mengikuti bujuk rayu setan.
Karena itu dalam Islam terdapat ajaran akhlaq tawassuthiyah (moderat), yaitu berada di tengah antara yang mengkhayalkan manusia sebagai malaikat yang menitikberatkan segi kebaikannya dan yang mengkhayalkan
manusia sebagai setan yang menitikberatkan sifat keburukannya saja.
Manusia memiliki dua kekuatan dalam dirinya: kekuatan baik yang berpusat pada hati nurani dan akalnya dan
kekuatan buruk pada hawa nafsunya.
Akhlaq Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan ruhani secara seimbang, serta memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara berimbang pula. Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat.
Keseimbangan dapat diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan semua komponen dalam suatu sistem dapat bekerja sesuai fungsinya.
Hidup berkesimbangan dapat terwujud apabila setiap elemen masyarakat dapat menjalankan fungsinya masing-masing (tugas dan kewajibannya) dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dalam al-Qur’an, Allah telah menyerukan agar manusia senantiasa berlaku adil (QS. 5:8), seimbang (QS. 55:9), moderat
(QS. 25:67), tidak berbuat aniaya pada orang lain (QS. 11:102), tidak memakan harta secara batil (QS. 2:188), tidak mengurangi takaran dan timbangan (QS. 83:1-3).
Kesemuanya dimaksudkan agar kehidupan manusia bermartabat, tercipta kedamaian, dan
senantiasa memperoleh ridlo dari Allah.
Puasa merupakan ibadah yang salah satu tujuannya mewujudkan keseimbangan di atas. Keseimbangan yang dapat mengantarkan manusia menjadi manusia paripurna (insan kamil), karena di bulan Ramadhan pintu ampunan dan kasih sayang Allah selalu terbuka.
Manusia paripurna yang lahir dari proses ritual ibadah puasa diidealkan dengan sosok yang telah meraih ketakwaan (la’allakum tattaqun) tingkatan tertinggi dengan menunjukkan kepribadian diri yang utuh dan terintegrasi.
Pada kondisi ini ketakwaan seorang hamba sudah mampu melindungi diri dari akibat-akibat perbuatannya sendiri yang berorientasi buruk, jahat, dan penuh tafsir kebencian.
Takwa dalam pemaknaan takut kepada Allah dengan pengertian takut kepada akibat-akibat perbuatannya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.
Eksternalisasi makna taqwa berupa personalitas rasa takut yang timbul karena bertolak dari kesadaran bahwa manusia memiliki tanggungjawab dunia-akhirat.
Selanjutnya terjadi proses dialektis ketika kesadaran manusia menjadi kesadaran diri tentang Yang Absolut dan ketika Yang Absolut mewujud dalam kesadaran manusia.
Kesadaran ilahiah manusia yang menggambarkan kenyataan historisnya merupakan replika pengalaman manusia yang
muncul dari keseluruhan beban nalar praktis dan teoritis keagamaannya.
Di sinilah moderasi pemahaman keagamaan memiliki peran signifikan mengingat adanya kemungkinan kecenderungan manusia mengadopsi ke dalam dirinya (introject) suatu proyeksi keagamaan yang diambil dari personalitas orang lain.
Puasa yang menghasilkan ketakwaan, dan ketakwaan yang mentransformasi seseorang menjadi manusia paripurna memiliki keunggulan dalam memegang prinsip-prinsip penegakan kebenaran, kebajikan, dan keindahan.
Sehingga gambaran cita ideal yang dicerminkan dalam perannya sebagai khalifah merupakan gabungan antara sifat-sifat
tersebut.
Manusia dengan cita ideal ini adalah manusia yang selalu tercerahkan dengan pola keimanan yang membuka diri dan humanis.
Secara aktual, hikmah puasa dapat diarahkan pada sebuah kategori intelektual yang mampu menggagas sistem keimanan yang tidak mengasingkan kebutuhan-kebutuhan manusia.
Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan secara logis bahwa agama dapat diselaraskan dengan landasan rasional. al-Din ‘aqlun la dina liman la ‘aqla lahu.
Tentu pemahaman ini harus diarahkan pada upaya melakukan purifikasi terhadap suatu pandangan yang disisipi elemen-elemen primitif dan barbar.
Dengan demikian masih ada pengakuan akan sublimasi ajaran agama yang tidak hanya berhenti pada konsep-konsep absolut, tetapi masih meyakini akan peran penting kontekstualisasinya.
Selanjutnya, endapan ilusi yang membius kesadaran kebergamaan harus ditempatkan kembali pada posisinya yang fitrah. Kesadaran yang memberikan peluang sebesar - besarnya untuk melakukan ta’amul dan tadabbur sehingga mampu melahirkan aktualitas-aktualitas yang bertolak dari pemahaman ketakwaan yang hakiki.
Di sinilah makna puasa menemukan momentumnya untuk melakukan kontrol (imsak). Imsak mengandaikan keseimbangan (al-tawazun) antara persepsi lahir dan persepsi batin, dunia dan akhirat.
Demikian pula, dengan imsak melarang perilaku yang ekstrem yang jelas-jelas membawa dampak negatif (QS. 28:77). Pemahaman ini tidak berarti bahwa hidup di dunia semata-mata mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau menolak begitu saja, melainkan memilih sisi yang lebih memberikan manfaat, tidak memberikan penyesalan di kemudian
hari, serta selamat dari ancaman siksa kelak di akhirat (al-Qusyairi).
Pemahaman keagamaan yang ekstrem selalu mengusung otoritas dan monopoli kebenaran. Argumentasinya dibangun di atas klaim kebenaran dengan cara menggeser kelompok lain yang dianggap berbeda dan bertentangan. Maka di tengah kehidupan global yang semakin kompleks dan plural, eksistensi agama semakin ditantang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan tersebut.
Dari sini spirit bulan suci Ramadhan harus terus digemakan sebagai bagian dari upaya menjawab dan menunjukkan kiprah dan peran agama pada bentuk hubungan sosial yang semakin dewasa. Kalau kenyataan ini yang terjadi, maka keinginan menjadikan agama sebagai landasan etis dalam mengatasi problem kemanusiaan kontemporer bukanlah suatu utopia belaka.
Bertolak dari keinginan menjalankan ibadah puasa dengan benar dan khusyuk kita mencoba memposisikan eksistensi kita pada pusat edar subjektivitas jagad raya yang ditransendensikan sepenuhnya pada kesadaran spiritual Ilahiyah. Ide ini menekankan dan menghargai nilai-nilai luhur humanisme-universal yang concern pada persoalan lingkungan hidup, etika sosial, dan masa depan kemanusiaan dengan mengandalkan pada penyatuan tadzakkur dan tafakkur.
Harapannya, keseimbangan unik yang terjadi karena aksi-aksi moral yang terintegrasi inilah puasa kita dapat mencapai nilai ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Allah a’lam. (*)